Kekerasan Simbolik Dibalik Drama Homo Academicus
Kerumunan anak di samping ruangan kelas itu sibuk membicarakan tentang tugas presentasi sebuah mata kuliah. Sesaat setelah itu, seorang dosen masuk kelas bersamaan dengan bubarnya kerumunan untuk masuk bersiap diri mempresentasikan hasil makalah yang beberapa hari sebelumnya dikerjakan dengan tidak terlalu serius, meskipun menyita banyak energi.
Presentasi dimulai. Lima anak yang tadinya berkerumun itu, berada di depan sambil membawa lembaran-lembaran kertas makalah yang sebelumnya sudah digandakan dan dibagikan ke seluruh mahasiswa. Singkat cerita, perdebatan mulai memanas. Mereka saling berdebat dan saling beradu argumentasi. Menonjolkan sisi rasionalitas dan sekian banyak referensi yang mereka pahami. Dan seperti kejadian yang sering terulang, diskusi menjadi sebuah perdebatan yang tak jelas arahnya: debat kusir. Pada saat demikian, dapat dipastikan mereka akan melegitimasi argumentasi masing-masing dan mengembalikan kepada otoritas penentu kebenaran dalam dinamika kelas. Siapa lagi kalau bukan dosen, meskipun penjelasan dosen pada mata kuliah sebelumnya sangat jauh dari apa yang mereka bicarakan. Dapat ditebak hasilnya, siapapun yang menjustifikasi perkataan dosen, dialah yang akan dimenangkan dan dibenarkan pendapatnya. Parahnya, ternyata dosen yang dijadikan simbol pembenaran argumentasi dinamika kelas itu kelihatan terlalu memaksakan pola penalarannya yang seringkali tidak konteks dengan apa yang menjadi akar permasalahan yang muncul. Semua akan tampak dari keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Sayangnya benar-salahnya dosen tak menjadi persoalan. Sebab bagaimanapun, mahasiswa yang menolak argumentasi dosen akan tetap diposisikan sebagai pihak yang salah. Padahal belum tentu apa yang diungkap mahasiswa yang kontraproduktif tersebut sepenuhnya salah. Bisa jadi sebaliknya. Bukankah segala pengetahuian mempunyai asas falsifikasi?
Penampakan wadak ketundukan tak beralasan mahasiswa ini adalah bukti dari adanya kekerasan simbolik peran-peran penjaga pengetahuan. Mereka (para dosen) seakan berposisi sebagai utusan Tuhan yang tak mempunyai cacat sedikitpun. Nyatanya, jika saja ada mahasiswa yang menyangkal apa yang diberikan dosen, akan tetap dianggap salah.
Drama realis seperti itu hampir pasti terjadi tiap hari. Ruang perkuliahan adalah panggung teater yang dipentaskan oleh mahasiswa sebagai peran pembantu, yang disutradarai dan diperan-utamai oleh sang dosen. Tak ada yang berani menolak, tak ada yang berani menentang dan tak ada seorang pun yang berani mengkritik.
Mahasiswa yang secara normatif-idealistik adalah agen penyebar kebenaran ilmu pengetahuan dengan perangkat kritis, progresif dan rasional senyatanya telah menjadi mekanisme yang disorganik. Mereka ibarat tabung kosong tanpa isi. Mereka menjadi komunitas yang diam tanpa pertahanan diri (self defense). Mereka adalah konfigurasi obyektif dari apa yang diungkap John Locke: Tabularasa.
(Civitas Akademik x Citra Pengetahuan) + Ranah Pendidikan = Kekerasan Simbolik
Dari penjabaran tersebut, anda pasti akan mengira bahwa dosenlah yang salah, dan mahasiswa jugalah yang bodoh. Tidak sesederhana itu, saudara! Anda harus ingat bahwa dosen tidak berdiri di ruang kosong dan mahasiswa hanya mewarisi kondisi dan budaya demikian secara turun-temurun.
Dalam hal ini, kita seniscayanya mengawali analisis tentang kekerasan simbolik dengan paradigma looking at the big picture. Dalam perspektif ini, dosen, mahasiswa adalah small picture dari konfigurasi komplek aturan pengetahuan yang tersistem.
Pertama, kita harus melacak mekanisme terbentuknya pola hubungan antar posisi dalam ranah pendidikan yang dalam hal ini terjadi antara dosen dan mahasiswa di tengah medan aturan kelas. Untuk itu kita harus membicarakan sistem apa yang berlaku dalam sebuah institusi pendidikan yang lebih besar.
Ruang kelas (Kosma) adalah satu domain yang di desain sedemikian rupa oleh regulasi (tata aturan) yang lahir dari pemegang kebijakan kampus. Sebut saja: pihak-pihak dekanat dan rektorat. Sistem itulah yang kemudian beroperasi membuat pranata dan moralitas kelas untuk senantiasa memposisikan dosen sebagai penjaga kebenaran yang otoritatif dengan berbagai hak privilege (hak istimewa) untuk mahasiswa. Kecenderungan taat dan patuh yang dipraktekkan oleh mahasiswa lebih didominasi oleh ketakutan mereka akan pemberian nilai oleh dosen. Sehingga orientasi keilmuan kemudian bergeser menjadi motivasi mencari nilai. Cara apapun dapat ditempuh oleh mahasiswa untuk merndapatkan nilai baik, yang salah satunya adalah sebisa mungkin menjauhkan diri dari konfrontasi dengan dosen.
Karena semenjak awal dosen telah diposisikan sebagai ‘manusia yang mampu’ mengekplorasi disiplin ilmu yang diberikan kepadanya, maka ia secara otomatis mempunyai citra pengetahuan sebagai ‘orang pintar’. Citra ini sebisa mungkin, dalam ketidakksadaran kolektif (collective unconsciousness) dosen untuk mempertahankan citra ini. Dalam rangka melakukan pertahanan citra (image defense) itu, dosen diberi hak memberi argumentasi apapun yang harus dibenarkan oleh mahasiswa. Potensi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh dosen menginjeksikan pemahaman keilmuiannya yang kadang ‘salah-kaprah’ kepada mahasiswa.
Sementara itu, mahasiswa diposisikan sebagai pihak yang harus menerima saja apapun petuah dosen. Sebab dalam wilayah ini mereka memahami bahwa prestasi akademis yang akan dibawanya diukur dari standarisasi angka-angka yang menjadi hak dosen untuk menilai. Apabila berbeda dengan frame kebenaran yang dimiliki dosen, dapat dipastikan mendapat nilai yang buruk. Untuk itulah, sekeras apapun kritik yang dilontarkan mahasiswa, mereka harus tetap mengalah jika tidak ingin diberi stigma sebagai mahasiswa yang reaksioner dan pembangkang. Bila itu terjadi, lagi-lagi ia harus rela mendapat nilai buruk. Inilah yang kemudian saya sebut dengan KEKERASAN SIMBOLIK dari penampakan teater kehidupan homo academicus.
Dari sini tampaklah bahwa dosen mempunyai modal simbolik dan modal sosial untuk mengkonstruksi realitas akademis dengan cara yang sedemikian halus. Modal simbolik yang kelihatan disini adalah klaim keilmuan dan modal sosialnya adalah deretan titel yang ada di depan maupun di belakang namanya. Dengan kedua modal itu, dosen menjadi sosok yang superior dan berhak memberi instruksi apapun seakan menjadi kebaikan mahasiswa. Padahal senyata, tidak sedikit dari pemberian instruksi dosen justru akan membingungkan, menyesatkan dan memaksa mereka memeras modal ekonomi untuk beberapa tugas makalah, kepingin CD hadits dan seabrek tugas lainnya. Kalau boleh jujur, rapuhnya sistem pendidikan ini bahkan dimanfaatkan oleh beberapa dosen sebagai ajang konsumerisme pendidikan. Tentu saja alatnya adalah mahasiswa.
Pada domain berbeda, pemegang kebijakan kampus menjadi penopang terjadinya ketidakberuntungan pendidikan kampus ini. Dengan menyerahkan sepenuhnya garis komando desain kelas kepada dosen, berarti dekanat sengaja cuci tangan atas sirkulasi keilmuan yang ada dalam kelas. Mereka lebih mementingkan urusan-urusan administrasi yang mekanistik dan verbalistik melalui pendisiplinan yang mereka anggap baik. Padahal pendisiplinan tidak hanya dipahami hanya sebatas strategi dalam mengatur dan mengarahkan suatu entitas masyarakat tertentu menuju tata aturan yang konstruktif. Sebaliknya ia niscaya dimaknai sebagai usaha untuk mengukuhkan suatu kekuasaan dan menyembunyikan kepentingan terselubung darinya.
Pendisiplinan di dalam ruang-ruang pengajaran yang didesain sedemikian formalistik dan verbalistik telah menjadi strategi menundukkan dan memberangus potensi kritis mahasiswa. Hingga relasi dosen-mahasiswa yang semestinya dijalin secara dinamis sebagai sama-sama subjek dalam pendidikan, dibalik menjadi subjek-objek. Dosen adalah subjek yang paling otoritatif untuk menyampaikan materi apapun yang wajib diterima oleh sang mahasiswa sebagai obyeknya tanpa reserve dan daya kritis. Singkatnya, insitusi pendidikan adalah tempat kondusif bagi bersarangnya pola-pola hegemoni dan dominasi.
Kedua, kekerasan simbolik hadir tidak hanya melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat formal dan verbalistik, melainkan juga melalui pengetahuan yang dikonseptualisasi sedemikian rupa untuk menjadi mesin kebenaran bagi vasted interest segelintir elit birokrasi. Krisis multidimensional adalah akibat kongkrit dari pola-pola demikian. Maka omong kosong dengan obyektifitas ilmu pengetahuan, jika realitas demikian adalah nuansa yang akrab dalam aktifitas keseharian kita di kampus. Solusinya, bagaimana anda berani menjadi aktor yang “beda” dalam drama realis ini. Wallahua’lam.
M. Zumrotul Abidin (Bulan kedua 2006)
Penulis adalah mahasiswa KI yang sedang meratapi diri menjadi obyek fetish rapuhnya sistem pendidikan Islam.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


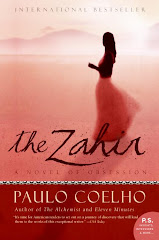





Tidak ada komentar:
Posting Komentar